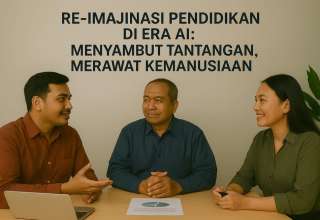*) Gambar sebagai ilustrasi
Selamat datang kembali di Podcast INOSI, ruang percakapan di mana ide-ide besar tentang pendidikan, teknologi, dan kemanusiaan diperdalam dan dipertautkan. Saya senang Anda bergabung hari ini karena kita akan membahas sebuah pertanyaan penting—bahkan mendesak—yang semakin relevan dari hari ke hari: Apakah mungkin kita berhenti melihat AI sebagai ancaman, dan mulai memanfaatkannya sebagai pembuka jalan menuju pembelajaran yang lebih manusiawi?
Sebelum kita menyelami episode hari ini, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi agar Anda tidak tertinggal episode terbaru kami, dan jika episode ini memberi Anda sesuatu untuk direnungkan, berikan like dan bagikan kepada para guru, pendidik, pembelajar, atau siapa saja yang peduli pada masa depan belajar.
Saat ini, banyak diskusi tentang AI dalam pendidikan terdengar seperti peringatan. Penuh kekhawatiran, penuh waspada, kadang bahkan bernada apokaliptik. Ada yang takut siswa tak akan belajar lagi karena semua bisa ditanyakan ke ChatGPT. Ada yang resah bahwa guru akan tergantikan oleh mesin. Ada pula yang mulai menyerah pada kualitas pembelajaran karena teknologi dianggap mempercepat tapi tidak memperdalam.
Tapi bagaimana jika kita mengubah lensa kita?
Bagaimana jika, alih-alih menganggap AI sebagai pemicu kehancuran pendidikan, kita mulai melihatnya sebagai pintu masuk—sebagai peluang besar untuk mentransformasi cara kita mengajar, belajar, dan membangun manusia yang utuh?
Di sinilah letak pergeseran utama: dari kecemasan menjadi keberdayaan. Dari resistensi menjadi desain ulang.
Mari kita bayangkan sebuah kelas masa depan. Kelas ini bukan didominasi layar dan gadget, tetapi diwarnai oleh proses berpikir yang aktif dan reflektif. Siswa tidak lagi dibentuk untuk menjawab soal dengan satu kunci jawaban. Sebaliknya, mereka dilatih untuk merancang pertanyaan eksploratif—pertanyaan yang terbuka, tajam, dan mengundang penelusuran lebih lanjut.
Pertanyaan seperti, “Bagaimana teknologi memengaruhi keadilan sosial di kotaku?” atau “Apa dampak dari satu keputusan ekonomi terhadap lingkungan hidup di desa saya?”
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak bisa dijawab dengan satu kali klik. Bahkan AI pun akan memberikan berbagai kemungkinan—karena kebenaran tidak tunggal, dan kontekslah yang menentukan nilai dari jawaban.
Inilah langkah pertama dari pembelajaran bermakna: menggeser fokus dari menjawab ke merancang pertanyaan. Ini adalah kompetensi yang akan tetap relevan bahkan ketika teknologi berkembang pesat. Karena hanya manusia yang bisa bertanya dengan penuh makna.
Langkah berikutnya dalam kelas masa depan itu adalah guru yang tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi membimbing siswa dalam memvalidasi dan menyesuaikan output AI dengan konteks mereka sendiri.
Ketika siswa meminta AI menjelaskan dampak revolusi industri, misalnya, guru akan mengajak mereka bertanya ulang: Apakah penjelasan ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Apakah kita bisa menemukan data lokal yang memperkuat atau menyanggah jawaban AI?
Dalam proses ini, AI bukan hanya mesin jawaban. Ia menjadi partner diskusi awal. Tapi dialektika, pemaknaan, dan penyelarasan tetap berada di tangan manusia—siswa dan guru.
Guru di sini hadir bukan sebagai pengoreksi, tetapi sebagai navigator pemaknaan. Inilah wujud peran baru guru yang lebih otentik: pemandu makna, bukan sekadar penyampai informasi.
Hal ketiga yang kita bayangkan dalam kelas masa depan adalah terbangunnya budaya dialog reflektif antara manusia dan AI.
Bayangkan jika siswa diminta membuat jurnal mingguan bukan hanya tentang topik yang dipelajari, tetapi juga tentang percakapan mereka dengan AI. Mereka merefleksikan bagaimana mereka mengajukan pertanyaan, bagaimana AI menjawab, apa yang mereka setujui dan tidak setujui, dan apa yang berubah dalam cara mereka berpikir.
Ini bukan hanya sekadar teknologi, ini adalah pembelajaran metakognitif—belajar tentang cara berpikir dan cara belajar.
Dan pada titik inilah kita melihat peluang besar AI dalam pendidikan: bukan untuk menggantikan proses manusia, tetapi untuk memperluas kesadaran manusia terhadap proses itu sendiri.
Semua contoh yang baru saja saya uraikan bukan imajinasi liar. Mereka adalah kemungkinan nyata—dan bahkan, sudah mulai diterapkan di berbagai komunitas belajar progresif. Namun agar ia bisa tumbuh secara luas dan sistematis, kita butuh kerangka kerja yang kuat dan fleksibel.
Di sinilah EXPLORE Framework masuk sebagai jawaban yang sangat relevan.
Framework ini dikembangkan oleh Mohamad Haitan Rachman sebagai respon atas kebutuhan mendesak dunia pendidikan masa kini. Dengan enam tahap pembelajaran yang terstruktur—Explore New Ideas, Practice Skills, Learn Deeply, Reflect Often, Organize Knowledge, dan Enrich Understanding—EXPLORE memberi kita cetak biru yang memampukan AI untuk berfungsi secara konstruktif dalam setiap tahapan belajar.
Mari kita telusuri lima langkah utama dalam konteks kelas masa depan tadi.
Pertama adalah Explore New Ideas. Di tahap ini, AI bisa menjadi mitra untuk menjelajahi gagasan-gagasan baru. Namun, bukan hanya menerima jawaban dari AI, siswa didorong untuk bertanya ulang, menggali lebih dalam, dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Guru memfasilitasi eksplorasi ini dengan memberikan ruang untuk keheranan dan diskusi terbuka.
Tahap kedua, Practice Skills, adalah fase di mana siswa mempraktikkan kemampuan yang relevan dengan dunia nyata. Di sinilah mereka dilatih menggunakan AI untuk menyusun rencana, mengolah data, atau menyusun argumen. Tapi praktiknya tidak berhenti di teknologi. Justru guru membimbing agar siswa mengekspresikan pemahaman mereka melalui proyek nyata, tulisan ulang yang dipersonalisasi, atau presentasi yang dikontekstualisasikan.
Lalu di tahap Learn Deeply, siswa diajak mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan realitas yang lebih luas. Ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil AI dengan sumber lain, berdiskusi dalam kelompok, atau bahkan mengundang narasumber lokal. Di sini, AI menjadi jembatan, bukan terminal.
Tahap berikutnya, Reflect Often, adalah jantung dari pembelajaran bermakna. Di sinilah siswa merenungkan apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan apa yang perlu diperbaiki. Mereka mungkin merefleksikan mengapa mereka setuju atau tidak dengan output AI, apa bias yang mereka temukan, atau bagaimana cara mereka bisa membuat pertanyaan yang lebih bermakna di lain waktu.
Dan terakhir, Enrich Understanding—di mana siswa didorong memperluas wawasan mereka. AI bisa memberikan akses ke sumber internasional, simulasi, atau studi kasus global. Tapi pemaknaan tetap terjadi ketika siswa mengaitkan itu semua dengan identitas, nilai, dan kontribusi mereka dalam kehidupan.
Sahabat INOSI, ketika kita memandang AI sebagai peluang, bukan ancaman, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut. Kita melihat bahwa teknologi bukan perampas nilai-nilai manusiawi—tapi justru dapat memperjelas dan memperkuatnya, jika kita mendesain pengalaman belajar dengan sadar.
Kita menyadari bahwa jawaban cepat dari AI bisa memicu pertanyaan lambat yang dalam. Bahwa ketepatan mesin bisa memancing refleksi manusia. Bahwa otomatisasi bisa mempercepat proses teknis, agar waktu dan tenaga kita bisa dipusatkan untuk yang paling bermakna: dialog, refleksi, dan relasi.
Namun, kita juga tidak naif. Integrasi AI yang bermakna dalam pendidikan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ia membutuhkan desain. Ia membutuhkan kepemimpinan. Ia membutuhkan keberanian untuk mengubah cara kita mengajar, cara kita menilai, bahkan cara kita melihat peran guru itu sendiri.
Kita harus melampaui logika “menggunakan AI di kelas”, menuju logika “mendesain ulang pengalaman belajar agar tetap manusiawi, meski didukung teknologi.”
Dan itulah sebabnya EXPLORE bukan hanya sekadar akronim. Ia adalah filosofi. Ia adalah cara melihat pembelajaran sebagai perjalanan: dimulai dari pertanyaan, dibentuk oleh praktik, diperdalam oleh refleksi, dan diperkaya oleh pemaknaan.
Mari kita akhiri episode ini dengan satu keyakinan sederhana tapi penting: AI bisa memberi jawaban. Tapi hanya manusia yang bisa memberi makna.
Maka tugas pendidikan hari ini bukan menyaingi teknologi, tapi membimbing generasi agar mampu berpikir, merasakan, dan bertindak dengan utuh di tengah dunia yang serba canggih.
Jika kita berhasil melakukan ini, maka AI bukan lagi musuh dalam kelas. Ia adalah sekutu yang memperkuat potensi belajar manusia—bukan untuk menjadikan kita seperti mesin, tapi justru untuk menjadikan kita lebih manusiawi dari sebelumnya.
Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Jika Anda merasa percakapan ini menyentuh pertanyaan-pertanyaan penting dalam benak Anda, mohon bantu kami menyebarkannya. Klik like, subscribe podcast INOSI di platform Anda, dan bagikan episode ini kepada siapa pun yang tengah berpikir ulang tentang pendidikan di era AI.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus bertanya, terus berefleksi, dan terus membangun pembelajaran yang bermakna.
Jika Anda ingin mengembangkan episode ini menjadi bahan presentasi, pelatihan guru, atau video edukatif, saya siap bantu menyesuaikan format dan audiensnya.
Jika mempunyai pertanyaan berkaitan dengan konten, pelatihan, pendampingan AI DISRUPSI PENDIDIKAN, dan juga kerjasama, silahkan kontak kami di haitan.rachman@inosi.co.id